 |
| a digital collage by me because using pantone 2016 colors is cool. (not sarcasm.) |
Seperti biasa, setiap pagi sebelum mulai bekerja saya selalu menyempatkan diri membaca berbagai macam artikel. Saat sedang mengubek-ubek tentang personal finance, saya menemukan artikel mengenai money lessons dari Forbes. Di situ dikatakan pentingnya memperkenalkan uang sejak dini.
Saya tumbuh besar di dalam keluarga yang bisa dibilang memanjakan. Mungkin karena saya anak pertama, dan orangtua juga berkecukupan, plus mindset orangtua — saya belajar untuk tidak memikirkan uang sejak kecil. Orangtua mengajarkan saya untuk tidak pernah memikirkan dari mana uang datang dan nilai uang. Saya bahkan tidak tahu membeli sesuatu harus memakai uang sampai saya kelas 1 SD. Biarpun orangtua saya tidak termasuk boros, hal ini membuat saya tidak mengenal uang dengan baik.
Masuk usia remaja, baru mata saya dibukakan soal uang. Pada masa itu, Ibu saya mulai sakit dan pengeluarannya cukup besar. Ayah juga mengalami penurunan penghasilan yang cukup signifikan. Puncaknya adalah sewaktu Ibu meninggal dan membuat monthly income praktis hanya digawangi Ayah saya sendiri saja. Saya mulai menyadari kalau untuk mendapatkan sesuatu tidak semudah dulu, dan saya tidak bisa menuntut kebutuhan finansial saya dengan gampang. Berbagai hal yang saya alami serta cara hidup orang di sekitar saya — seperti teman-teman keluarga — helped me shaping my current perspective about money and financial. Ada pelajaran yang saya ambil dari cara orangtua dan keluarga dalam menghadapi uang; baik dari yang mereka lakukan, maupun tidak mereka lakukan.
You may have to wait to buy something you want. (and need, eventually.)
Biarpun orangtua saya tidak mengajarkan uang sejak dini, orangtua saya mengajarkan untuk hanya membeli apa yang dibutuhkan. Setiap kali hendak membeli sesuatu yang mahal (sebut itu gadget, atau konsol, atau barang seperti sepatu dan tas) Ayah selalu bertanya apakah barang yang lama sudah rusak. Apabila masih bisa dipakai, atau relevan, maka barang tersebut wajib dipakai sampai titik darah penghabisan. Biarpun Ayah juga kadang suka memanjakan saya bersaudara dengan memberikan hadiah mendadak, hal ini cukup mengajarkan saya untuk tidak membeli impulsif. Menahan diri sebelum membeli sesuatu dan memikirkan ulang setiap kali akan melakukan pembelian adalah salah satu cara ampuh untuk menahan dompet jebol. Kita tidak perlu membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan.
Memiliki tabungan sangat penting karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan.
Generasi Milenial dikatakan memiliki kecenderungan untuk menabung lebih banyak dari generasi sebelumnya. Hal ini bisa jadi dikarenakan kita sudah melewati masa resesi. Saya sendiri berkaca dari orangtua: orangtua saya punya tabungan, tapi semua habis sewaktu Ibu saya sakit dan mengeluarkan biaya yang setara dengan rumah mewah di perumahan eksklusif. Selain itu, tidak adanya Ibu juga membuat pemasukan rumah hanya berasal dari satu orang, dengan Ayah saya yang berstatus sebagai wiraswasta. Kondisi keuangan jadi tidak dapat terprediksi dan rasanya seperti dikejar hal yang tak terlihat. Hal ini dapat berpengaruh pada produktivitas dan kesehatan.
Karena itu, dari segala hal mengenai uang, tabungan adalah prioritas saya. Sebelum berpikir soal investasi, deposito, apalagi mengucurkan uang muka kredit kendaraan, menabung ada di urutan pertama. Jangan sampai kita tidak punya dana darurat sama sekali. Idealnya, dana darurat adalah setara dengan 3-4 bulan kebutuhan per bulan, dan jangan disentuh sama sekali kecuali dalam keadaan benar-benar darurat.
Kartu kredit itu kebutuhan tersier.
Sebagai anak biasa yang terpengaruh sinetron di televisi, ketika SD, saya selalu berpikir orangtua saya miskin — karena mereka tidak punya kartu kredit barang sebuah pun. Setiap bulan penawaran kartu kredit datang via pos, yang langsung dirobek. Ibu saya pernah membatalkan pembelian barang elektronik di sebuah mal karena hanya bisa dibeli menggunakan kartu kredit. Saya pikir, kok begitu? Kok Ibu nggak keren kayak orang-orang di televisi yang tinggal ngeluarin kartu? (Well people, this is what sinetron taught you…)
Setelah besar, saya baru mengerti mengapa mereka tidak menggunakan kartu kredit. Kartu kredit lebih banyak mengundang orang untuk memiliki budaya konsumtif dibanding iming-iming yang dijanjikan penerbitnya, seperti kemudahan membayar atau bonus voucher makan. Lagipula, untuk dapat bonus, kita harus berbelanja lebih dulu. Bukankah akan lebih hemat kalau kita tidak berbelanja sama sekali? ;)
Memang sih, selama kita bisa menggunakan kartu kredit secara tepat, menggunakan kartu kredit bisa bermanfaat, bahkan menguntungkan. But I know fairly well about myself that I choose to not using any credit card. Satu-satunya yang bikin saya sedih karena saya nggak punya kartu kredit, adalah karena saya nggak bisa bikin paypal. Untungnya, sekarang beberapa Bank di Indonesia menyediakan layanan virtual credit card (VCC) sehingga akun paypal dapat diverifikasi serta menggunakan kartu debit.
Hidup hemat dan seperlunya.
“Hemat" ini pengertiannya bisa berbeda bagi setiap orang. Begitu juga dengan perlu. Seringkali kita menipu pikiran sendiri dengan menyatakan "perlu", padahal kenyataannya tidak. Beli sepatu lagi karena yang lama sudah kusam, atau butuh hak yang lebih tinggi. Butuh buku yang seakan-akan harus dibeli karena dapat mengubah jalan hidup. Kasus yang sudah umum terjadi adalah butuh ganti barang/gadget karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.
Memang, faktor utamanya adalah karena situasi dan kondisi keuangan yang membuat saya memilih untuk tidak membeli barang baru. Tetapi mengingat ada banyak orang yang terjebak membeli barang baru dengan hutang, maka kebiasaan ini jadi menguntungkan. Saya terbiasa untuk berpikir dengan uang tunai (karena orangtua saya tidak mengajarkan saya untuk berhutang, dan mereka juga jarang sekali melakukan hal tersebut), sehingga dengan sendirinya belanja pun cenderung lebih sedikit.
Faktor kelemahan pola pikir ini bagi saya adalah saya mudah sekali membuang-buang uang untuk makanan. Karena nominalnya pasti lebih sedikit dari gadget atau make-up, maka saya rela-rela saja membuang uang untuk makanan yang agak mahal. Padahal kalau diakumulasikan dalam setahun.... sepertinya cukup tuh, untuk beli gadget baru atau yang lainnya. Maka, tahun ini saya sedang berjuang agar tidak mudah tergoda jajanan.
Tulis jurnal keuangan pribadi, dan jadikan itu pedoman.
Ini adalah yang paling penting. Dulu, Ibu saya adalah orang yang rajin mencatat; beliau punya buku agenda tebal yang berisi daftar pemasukan dan pengeluaran. Dari situ, saya bisa mengintip dan tahu kapan saya bisa mendapatkan apa yang saya minta pada Ibu; bulan ini atau bulan depan, pasti ada catatannya. Ayah saya bukan orang yang gemar mencatat. Beliau adalah orang yang termasuk tidak hitungan. Keuangannya mengalir seperti air, dan seperti yang saya perhatikan sendiri, situasi finansialnya juga seperti air yang tidak diwadahi dengan baik. Kadang meluap, kadang gersang dan kering.
Mencatat pemasukan dan pengeluaran ibarat memberi wadah untuk air; kita bisa tahu seberapa banyak yang kita butuhkan dan seberapa banyak yang dapat kita simpan. Mencatat bisa menggunakan metode tradisional, yaitu buku tulis dan pulpen (add an oldie-goodie calculator, kayak ibu kos di film-film zaman dulu), atau metode digital, alias menggunakan aplikasi spreadsheet. Karena saya adalah orang yang lumayan pemalas apabila harus mencatat dengan detail, maka saya menggunakan aplikasi ponsel. Sudah hampir dua tahun saya menggunakan Monefy.
Dengan mencatat pengeluaran dan pemasukan secara rinci, kita dapat melihat situasi keuangan secara telanjang. Berapa yang masuk, berapa yang keluar, kategori mana yang pengeluarannya paling besar dan apa yang dapat kita lakukan untuk menguranginya. Data is knowledge and knowledge is power.
Beramal dan membayar pajak.
Saya melihat ini dari Ayah saya. Ayah saya juga tidak pernah abai membayar pajak, jauh sebelum ketika pembayaran SPT pajak pribadi dipromosikan heboh seperti saat ini. Latar belakang pekerjaannya di bidang pajak juga berpengaruh, memang. Lalu, seperti sudah dijelaskan di atas, Ayah saya bukan oang yang perhitungan. Apabila ada yang meminta bantuan, baik keuangan atau lainnya, beliau akan langsung membantu — dan seringkali membuat neraca keuangan sedikit timpang, kalau saya lihat. Saya sendiri, kadang gemas karena Ayah begitu mudah memberi. Maklum, saya orang yang
Memang, ada kalanya neraca keuangan jadi timpang karena kejadian tersebut. Tetapi juga selalu ada yang membantu. Entah temannya, entah keluarganya. Ayah punya jangkauan pertemanan yang luas dan berasal dari berbagai macam kalangan. Kami tidak pernah berkenalan dengan rentenir biarpun situasi keuangan naik turun. Selalu ada teman Ayah yang berbaik hati membantu. Hal ini memang tidak berkaitan langsung dengan uang; namun secara tidak langsung Ayah mengajarkan bahwa ada yang lebih besar daripada uang. Silaturahmi dan rasa kekeluargaan. Memberi tidak akan pernah membuat kita rugi.
Over the years, what sticks the most in my head is money is merely a tool. Sebuah alat yang harus digunakan dengan baik agar manfaatnya bisa terasa maksimal. Alat dengan kemampuan yang luar biasa. Dengan menggunakan uang secara tepat bisa mengantarkan kita menuju kebebasan dan rasa aman. Tetapi, biarpun uang memiliki kekuatan yang besar untuk mengubah suatu hal, pada akhirnya dia hanyalah sebuah alat. Kebahagiaan dan kepuasan tetap berasal dari kita sendiri. My parents may be not the perfect people to teach their children about money, namun ada banyak pelajaran yang dapat diambil dari cara mereka menghadapinya.
Segalanya memang butuh uang, tapi uang juga bukan segalanya. Selagi sekarang saya berjuang untuk memanfaatkan uang secara maksimal, saya juga tidak boleh putus asa atau diperalat oleh uang. Don't you feel the same way? :)

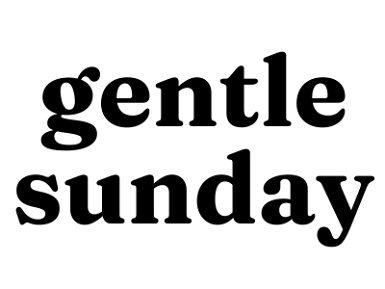
Komentar
Posting Komentar